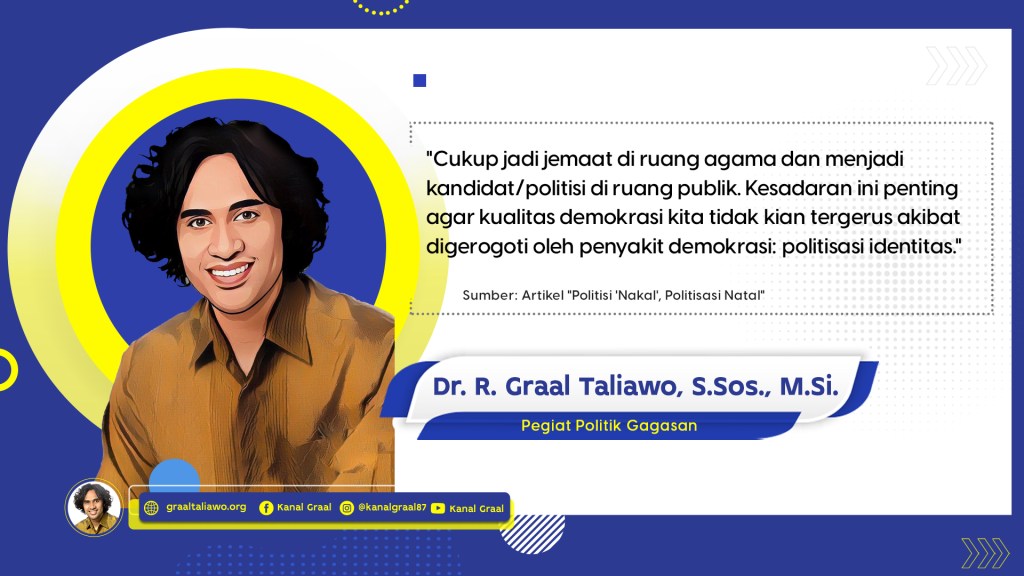BELAKANGAN ini Maluku Utara kembali ramai diperbincangkan, baik lokal maupun nasional. Isu sentralnya seputar aktivitas pertambangan yang bergeliat di daerah ini. Kita pun digiring pada kutub ekstrem: pro sepenuhnya atau kontra sepenuhnya. Poin plus dari aktivitas pertambangan memang tidak bisa diabaikan begitu saja, namun tentu ini bukan pilihan untuk jangka panjang karena sifat destruksi atasnya. Saya tidak ada pada kedua posisi ekstrem tersebut, melainkan di posisi yang lain: jeda pertambangan dan menggiatkan sektor sumber daya alam berkelanjutan: perikanan, pertanian/perkebunan.
Kenapa mengeksplorasi tambang?
Sementara ini Pemerintah tidak punya modal/kapital untuk membangun negara seorang diri. Dibutuhkan orang kaya/investor untuk berinvestasi. Dari investasi inilah, negara mengantongi akumulasi kapital melalui pajak dan bukan pajak. Pertambangan masuk opsi untuk dieksplorasi karena, salah satunya, ‘barang’ ini begitu dilirik investor dan pasar. Lebih cepat mendapatkan keuntungan, sebab akumulasi kapital banyak berputar di sana.
Pertambangan disebut-sebut sebagai kontributor terbesar bagi sumber pendapatan negara dalam waktu yang tergolong singkat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (15/01/2024) merilis realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM mencapai Rp 300,3 triliun pada 2023. Mineral dan batu bara menyumbang 58% dari total tersebut, yakni Rp 173 triliun. Melesat tajam jika pendapatan dari pajak ikut dihitung.
Ekonomi negara, termasuk daerah, sudah pasti kecipratan. Ini menjadi modal untuk pembangunan di berbagai bidang publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Harapannya, bisa linier dengan kesejahteraan warga melalui hak-hak publiknya yang berangsur terpenuhi.
Besarnya aktivitas pertambangan terbukti mampu menyerap tenaga kerja secara massal. Ini bersambut positif dengan angka pengangguran di Indonesia (juga Maluku Utara) yang cukup tinggi. Kesempatan kerja terbuka dengan upah yang biasanya di atas rata-rata (dibandingkan bidang kerja umumnya).
Selain itu, masifnya aktivitas pertambangan turut membuka kesempatan bagi usaha-usaha pendukung. Kos-kosan, transportasi umum, warung makan, toko sembako, dan kebutuhan sandang, pangan, papan lainnya. Geliat dan perputaran ekonomi daerah akan hidup. Bank Indonesia mencatat pada 2022 Maluku Utara mengalami akselerasi pertumbuhan ekonomi 22,94% (djpb.kemenkeu.go.id, 13/04/2023).
Poin plus yang juga dirasakan adalah adanya penambahan/transfer pengetahuan terkait dunia pertambangan dan teknologi. Masyarakat bisa mengenal hal-hal modern, misalnya sistem komputerisasi peralatan yang bisa mengefisienkan dan mengefektivitaskan aktivitas manusia. Ke depan, ini membantu kita sebagai negara kaya tambang untuk kelak bisa mengeksplorasinya secara mandiri.
Terimpit ancaman tambang
Tak melulu berdampak positif, industri ekstraktif ini telah dilabeli sebagai industri yang mengotori bumi. Isu terbesar yang mengonfrontasinya adalah lingkungan. Ini yang diresahkan warga dan penolakan terus berdatangan atasnya. Konflik persinggungan lahan kerap terjadi antara lahan pertambangan dengan lahan masyarakat adat, masyarakat lokal, atau area hutan lindung. Ini juga terjadi di beberapa kabupaten di Maluku Utara: suku Tobelo Dalam di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, konflik Gunung Wato-wato di Halmahera Tengah, konflik warga desa dengan perusahaan tambang di Desa Bobo, Halmahera Selatan, dan lainnya.
Tambang butuh lahan yang luas, tak jarang bersinggungan dan berdekatan dengan lingkungan warga. Pembebasan lahan tambang—termasuk praktik deforestasi—sudah lazim berkonflik dengan warga sekitar, tak terkecuali masyarakat adat. Global Forest Watch (kompas.id, 19/06/2024) mendata selama 2001–2023 Maluku Utara kehilangan tutupan pohon hutan sebesar 258.000 hektare akibat alih fungsi lahan pertanian ke pertambangan. Lahan pertanian/perkebunan krisis. Dinas Pertanian Maluku Utara mencatat ada 27.959 ha Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, begitu jauh dibandingkan dengan lahan konsesi tambang yang mencapai 655.581 ha (Jatam, 2024).
Sampai April 2025 ada 115 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku Utara). Pulau Taliabu hampir seluruh wilayahnya sudah masuk IUP, pun Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 50% dari luas wilayahnya.
Mutlak, lingkungan dan ekosistem sudah pasti akan terdampak. Pencemaran, polusi, dan limbah atas tanah, air, dan udara. Semua ini notabenenya adalah wadah/tempat mata pencarian untuk warga. Pun hak warga atas kesehatan lingkungan tercerabut. Perairan Halmahera, yang padahal adalah area Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) nasional, tercemar logam berat. Hasil uji lab terhadap sampel ikan yang berasal dari Teluk Buli dan Teluk Weda menunjukkan ikan tidak dalam kondisi sehat (kompas.id, 07/11/2023). Ada sel dan jaringan yang rusak pada hati, ginjal, dan daging.
Efek lainnya adalah pergeseran lanskap pola hidup dan budaya kerja warga. Dari sistem mata pencarian tradisional ke modern. Akan berbahaya jika tanpa transisi pengetahuan. Mereka akan gagap karena belum terbiasa dan belum beradaptasi. Tak jarang, posisi paling banter yang didapat warga sekitar adalah tenaga kerja kasar yang tinggi risiko. Dampaknya bisa fatal sampai pada kecelakaan kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku Utara mencatat ada sekitar 155 kasus kecelakaan kerja sepanjang 2022 yang sebagian besarnya berlokasi di lokasi pertambangan.
Prostitusi dan kriminalitas mengekor. Pekerja yang sebagian besarnya adalah laki-laki dan jauh dari keluarga potensi menyalurkan hasrat seksualnya kepada pekerja seks komersial. Bahaya jika ini menjerat mereka yang di bawah umur dan potensi merebaknya penyakit seksual menular. Ketimpangan sosial antarpekerja, dengan warga, atau dengan pihak lain melahirkan sentimen ketidakadilan. Kerapkali berujung pada kriminalitas berupa pencurian, perusakan, dan seterusnya.
Jeda pertambangan
Ibarat timbangan, kedua sisi dari aktivitas pertambangan ini bermuatan. Naif bila mengelak dampak negatifnya dan tidak adil jika mengabaikan dampak positifnya. Namun, adanya dampak negatif cukup menjadi alasan untuk perlu mengembangkan alternatif ekonomi di luar pertambangan; tidak hanya menjadikan tambang sebagai pilihan utama jangka panjang dalam berkontribusi terhadap pendapatan negara.
Perlu selalu diingat, tambang dan mineral lainnya adalah kategori sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, jika dikeruk terus-menerus akan habis—tak tersisa, kecuali jejak pengrusakannya. Deforestasi di mana-mana (bahkan meluas) untuk beralih fungsi menjadi lahan pertambangan. Imbasnya, unsur vital seperti cadangan oksigen dan keanekaragaman hayati lainnya ikut terancam. Ini tentu dampak yang serius. Padahal, di masa depan anak-cucu kita tentu masih membutuhkannya. Kurang bijak jika kita bersikap serakah mengeruknya pada masa sekarang tanpa ada tanggung jawab menyimpan cadangannya untuk kemudian hari.
Di tengah kondisi sekarang ini, jeda menerbitkan IUP adalah opsi yang perlu dipertimbangkan. Konkretnya dimulai dengan menjeda untuk mengeluarkan IUP dan konsesi yang baru. Fokus untuk mengembangkan IUP dan konsesi yang sudah diterbitkan. Sembari itu, pemerintah perlu putar otak dan berinovasi untuk meningkatkan pendapatan negara dengan ekses negatif (yang ditimbulkan) sekecil mungkin. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencari dan mengedepankan sumber daya eksplorasi lain yang lebih ramah dan berkelanjutan.
Kedepankan semangat berinovasi dan berkreasi untuk menggenjot sektor-sektor lainnya yang low risk, high return. Salah satunya investasi hijau: perikanan, pertanian/perkebunan. Karena sudah pasti ini lebih berdampak positif dari kacamata lingkungan dan ekosistem. Misalnya, lahan yang ada bisa saja dimanfaatkan untuk menanam vegetasi tertentu sebagai alternatif energi terbarukan pengganti tambang dan mineral lainnya. Contoh, ada bahan bakar dari tumbuhan (campuran alkohol dari tanaman tebu) yang sudah diujicobakan. Pertambangan cukup dieksplorasi untuk jangka pendek sebagai modal. Selanjutnya diberi jeda. Beriringan dengan itu, pemerintah dengan memanfaatkan teknologi fokus mengeksplorasi sumber daya alam berkelanjutan di sekitar. Maluku Utara kaya akan perikanan dan pertanian/perkebunan, juga pariwisata. Ketiga sektor ini bisa menjadi pilihan utama untuk menggenjot sumber pendapatan negara melalui penguatan dan pengembangan atasnya. Sudah pasti ekses negatif seperti yang disebutkan di atas sangat mungkin untuk diminimalisasi.
*Artikel ini telah dipublikasikan di kompas.com, 12/05/2025, https://money.kompas.com/read/2025/05/12/073424126/jeda-tambang-kembangkan-alternatif